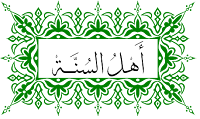1. Pengertian dan nama-nama Ilmu Perbandingan Agama.
Ilmu Perbandingan Agama adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala keagamaan dari suatu kepercayaan (agama) dalam hubungannya dengan agama lain. Pemahaman ini mencakup persamaan (kesejajaran) dan perbedaannya. Selanjutnya dengan pembahasan tersebut, struktur yang asasi dari pengalaman keagamaan manusia dan pentingnya bagi hidup dan kehidupan manusia dapat dipelajari dan dinilai ( Ali, 1975: 5).
Di samping nama Ilmu Perbandingan Agama, ada beberapa nama lain dari Ilmu perbandingan Agama. Nama-nama tersebut antara lain:
Allgemeine Religionswissenschaft, Science of Religions, The History of Religions, Comparative Studies of Religion, Phenomenology of Religion, Historical Phenomenology, The Study of World Religions dan The Comparative Study of Religions (Daya dan Beck, 1990: 57),
Systematic Science of Religion (Daya dan Beck, 1992: 30),
Vergleichende Religionswissenschaft (Daya dan Beck, 1992: 165),
Ilmu Agama-agama (Daya dan Beck, 1990: 28),
Ilmu Agama, Sejarah Agama, Fenomenologi Agama (Daya dan Beck, 1990: 126). Dari beberapa nama tersebut nama
Phenomenology of Religion dan
Fenomenologi Agama kadang-kadang digunakan untuk nama suatu bidang studi tertentu yang lebih sempit cakupannya dari studi Ilmu Perbandingan Agama, yaitu mengkaji agama dengan metode fenomenologis saja.
Berdasarkan nama-nama lain dari Ilmu Perbandingan Agama di atas, jelaslah bahwa Ilmu Perbandingan Agama tidak hanya membanding-bandingkan agama saja, tetapi juga melakukan kajian historis, fenomenologis, atau secara umum melakukan kajian yang bersifat ilmiah atau scientific. Hal itu akan semakin jelas setelah dibahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam Ilmu Perbandingan Agama.
2. Obyek Ilmu Perbandingan Agama
A. Mukti Ali, seorang pakar Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, menjelaskan bahwa obyek Ilmu Perbandingan Agama adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fundmental dan universal dari tiap-tiap agama. Beberapa pertanyaan tersebut akan akan dijawab sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Beberapa pertanyaan yang bersifat fundamental dan universal tersebut antara lain: apakah konsepsi agama tentang Tuhan? Apakah konsepsi agama tentang manusia? Apakah konsepsi agama tentang dosa dan pahala? Apakah hubungan kepercayaan dengan akal? Bagaimanakah hubungan antara agama dengan etika? Apakah fungsi agama dalam masyarakat? dsb. ( Ali, 1975: 7).
Berbeda dengan A. Mukti Ali, Joachim Wach dari sudut pandang yang lain, berpendapat bahwa obyek Ilmu Perbandingan Agama adalah pengalaman agama. Menurut Joachim Wach pengalaman agama berbeda dengan pengalaman psikis biasa. Pengalaman agama mempunyai beberapa kriteria tertentu. Kriteria pertama, pengalaman agama merupakan suatu tanggapan terhadap apa yang dihayati sebagai Realitas Mutlak. Kedua, pengalaman agama merupakan tanggapan yang menyeluruh atau utuh (akal, perasaan, dan kehendak hati) manusia terhadap Realitas Mutlak. Ketiga, pengalaman agama merupakan pengalaman yang paling kuat, menyeluruh, mengesankan, dan mendalam dari manusia. Keempat, pengalaman agama merupakan pengalaman yang menggerakan untuk berbuat. Pengalaman tersebut mengandung imperatif, menjadi sumber motivasi dan perbuatan yang tak tergoyahkan (Wach, 1969: 31-36). Pengalaman agama yang subyektif ini diekspresikan atau diungkaplan dalam tiga ekspresi, yaitu: a. pengalaman agama yang diungkapkan dalam pikiran. b. pengalaman agama yang diungkapkan dalam tindakan. c. pengalaman agama yang diungkapkan dalam kelompok (Wach, 1969: 97). Pengalaman agama yang diungkapkan dalam pikiran terutama berupa
mite, doktrin, dan
dogma. Pengalaman agama ini dapat berbentuk
symbol,
oral, dan
tulisan.
Tulisan-tulisan
bisa berupa
kitab suci dan tulisan
klasik Untuk keperluan memahami kitab suci diperlukan literature yang sifatnya menjelaskan, misalnya
Talmud, Zend dalam Pahlevi,
Hadis dalam Islam,
Smrti di India, tulisan-tulisan Luther dan Calvin dalam Protestan. Agama-agama besar juga mempunyai
credo, yaitu suatu ungkapan pendek tentang keyakinan,
syahadat dua belas dalam Kristen,
dua syahadat dalam Islam, dan
shema dalam Yahudi. Adapun tema yang fundamental dalam pengalaman agama yang diungkapkan dalam pikiran adalah Tuhan, kosmos, dan manusia (
Teologi,
kosmologi, dan
antropologi). Selanjutnya pengalaman agama yang diungkapkan dalam tindakan berupa
kultus (peribadatan) dan pelayanan. Peribadatan sebagai tanggapan terhadap Realitas Mutlak harus dilakukan di mana, kapan, bagaimana caranya, dan oleh siapa? Apakah ibadah itu harus dilakukan sendiri-sendiri atau secara berjamaah? Termasuk dalam uangkapan perbuatan ini adalah kurban dengan segala seluk-beluknya. Termasuk dalam pembahasan ini adalah maslah
imitation, yaitu mencontoh tingkah laku dan kehidupan seorang pemimpin agama. Termasuk dalam pembahasan ini adalah keinginan supaya orang lain juga beragama seperti dia, yaitu masalah
missionary atau
dakwah. Akhirnya pengalaman agama yang diungkapkan dalam kelompok berupa kelompok-kelompok keagamaan (
Ecclesia atau
Gereja,
Kahal, Ummah,
Sangha). Di sini dibahas juga masalah hubungan antara orang yang beragama dengan masyarakat umumnya, bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan mereka baik
antar-agama maupun
intra-agama sendiri, fungsi,
kharisma, umur, seks, keturunan, dan
status (Ali, 1993: 79-81).
Ketiga ekpresi pengalaman agama di atas (pikiran, tindakan, dan kelompok) yang menjadi obyek Ilmu Perbandingan Agama meliputi semua agama yang ada dan aliran-alirannya.
Kedua pandangan di atas dapat digabungkan sebagai obyek Ilmu Perbandingan Agama. Pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dan universal bagi setiap agama dan pengalaman agama, keduanya merupakan aspek-aspek penting dari obyek Ilmu Perbandingan Agama.
3. Metode-metode Ilmu Perbandingan Agama.
Ada beberapa metode yang digunakan dalam Ilmu Perbandingan Agama. Metode-metode tersebut ialah:
1. Metode Historis.
Dalam metode ini agama dikaji dari segi atau aspek periodesasi dan saling pengaruh antara agama yang satu dengan agama lainnya. Di sini dikaji asal-usul dan pertumbuhan pemikiran dan lembaga-lembaga agama melalui periode-periode perkembangan sejarah tertentu, serta memahami peranan kekuatan-kekuatan yang diperlihatkan oleh agama dalam periode tersebut (Wach, 1969: 21).
Agama yang dikaji dalam metode ini bukan hanya agama secara keseluruhan, tetapi juga dapat dikaji aliran-aliran tertentu dari suatu agama maupun tokoh-tokoh tertentu dari suatu agama dalam periode tertentu dalam sejarah (Jongeneel, 1978: 49).
Bahan dalam kajian in biasanya mempergunakan bahan primer dan sekunder, baik yang bersifat literer (
filologis) atau non-literer (
arkeologis) (Jongeneel, 1978: 51).
Beberapa contoh kajian histories misalnya kajian C.J. Bleeker dan G. Widrengen dalam bukunya
Historia Religianum, Handbook for the History of Religious. R.J.Z. Werblowsky dalam bukunya
Histoire des Religions. Ugo Bianchi dalam bukunya
La Storia delle Religioni. J.P. Asmussen dan J. Laessoe dalam bukunya
Handbuch der Religiongeschichte. H. Ringgren dan A.V. Strom dalam bukunya
Religious of Mankind. Today and Yesterday. T.O. Ling dalam bukunya
History of Religion East and West. E. Dammann dalam bukunya
Grundriss der Religionsgeschichte, dan S.A. Tokarev dalam bukunya
Die Religion in der Geschichte der Volker (Whaling, 1984: 57-63).
Para sarjana yang mempergunakan metode historis ini antara lain: C.J. Bleeker, G. Widrengen, A. Reviolle, A. Bertholet dan Fr. M. Muller (Jongeneel, 1978: 59).
2. Metode Sosiologis.
Dalam metode ini dikaji problem-problem agama dan masyarakat dalam hubungannya satu sama lainnya. Banyak yang dapat dikaji dalam metode ini. Misalnya pengaruh kehidupan masyarakat dan perubahan-perubahannya terhadap pengalaman agama dan organisasi-organisasinya; pengaruh masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama, praktek-praktek agama, golongan-golongan agama, jenis-jenis kepemimpinan agama; pengaruh agama terhadap perubahan-perubahan sosial, struktur-struktur sosial, pemenuhan atau fustrasi kebutuhan kepribadian; pengaruh timbale balik antara masyarakat dengan struktur intern persekutuan agama (segi keluar-masuknya jadi anggota, segi kepemimpinannya, toleransinya, kharismanya, dsb.); pengaruh gejala-gejala kemasyarakatan (
mekanisasi,
industrialisasi,
urbanisasi, dsb.) terhadap agama; pengaruh agama terhadap etik, hukum, negara, politik, ekonomi, hubungan-hubungan sosial, dsb. (Jongenel: 1978: 68-69).
Beberapa contoh dari metode sosiologis ini misalnya: kajian Emile Durkheim mengenai hubungan totem dengan masyarakat. Menurut Emile Durkheim bentuk dan macam
totem tergantung pada bentuk masyarakat. Dalam kajian lainnya ia menghubungkan antara gejala bunuh diri dengan Katolik dan Protestan. Menurutnya gejala bunuh diri di kalangan Katolik lebih sedikit dibandingkan di kalangan Protestan. Hal itu terjadi karena masyarakat di kalangan Katolik lebih banyak tergantung pada
tradisi, sehingga problem-problem yang menimpa anggota-anggotanya dapat diselesaikan melalui tradisinya. Sedang di kalangan Protestan lebih bersifat individual, sehingga problem-problem yang menimpa anggota-anggotanya terpaksa dipecahkan secara individual.
Contoh lainnya misalnya kajian Max Weber dalam bukunya
The Protestan Ethic and the Spirit of Capitalism tentang hubungan antara ajaran etik Protestan dengan sikap kapitalis (Nottingham, 1985: 136-137). Renato Poblete SJ dan F. O’Dea dalam penelitiannya pada para imigran Puerto Rico di New York dengan judul “Anomie and the Quest for community,” The Formation of Sects among the Puerto Ricans of New York,” menjelaskan bahwa konversi pemeluk Gereja Katolik ke gereja Pentecostal bermotif pembebasan dari krisis sosial dan situasi anomi yang menimbulkan krisis batin (Hendropuspito, 1986: 85-86).
Beberapa sarjana yang menggunakan metode sosiologis antara lain: Joachim Wach, Milton Yinger, G. Le Bras, Gustav Mensching, (Jongeneel, 1978: 69), Fustel de Coulangers, Emile Durkheim, Max Weber, Ernst Troeltsch, Werner Sombart, Max Scheler (Wach, 1969: 23).
3. Metode psikologis.
Di sini dikaji aspek batin dari pengalaman agama individu maupun kelompok (Wach, 1969: 23). Di dalam metode ini dikaji interrelasi dan interaksi antara agama dengan jiwa manusia (Jongeneel, 1978: 86). Kajian psikologis ini meliputi masalah
arketipus, symbol,
mite,
numinous,
penyataan (wahyu), iman, pertobatan,
revival, suara hati, keinsafan dosa, perasaan bersalah, pengakuan dosa, pengampunan, kekhawatiran, kebimbangan, penyerahan diri, kelepasan,
askese, kesucian,
mistik,
meditasi,
kontemplasi,
ekstase, orang-orang
introvert agama, orang-orang
ekstrovert agama, kehidupan jiwa orang-orang
psikose,
psikopati,
neurose, dsb
Beberapa contoh dari penggunaan metode psikologis misalnya: kajian agama yang dilakukan oleh J. M. Charcot dan P. Janet. Mereka menyimpulkan bahwa agama dapat dijabarkan terutama kepada
neurose dan
histeri. Sigmund Freud menyimpulkan bahwa agama harus dipandang sebagai suatu gejala dari tahun-tahun masa kecil yang hidup terus dalam kedewasaan, suatu ketidakdewasaan yang kolektif, suatu
simtom neurotis, suatu impian, suatu
illusi. W. Wund berpendapat bahwa agama ditinjau dari segi asal-usulnya merupakan gejala yang berhubungan dengan kehidupan jiwa bangsa, bukan kehidupan jiwa individu. William James menyimpulkan bahwa orang
healthy minded soul dapat mengembangkan diri secara selaras, sedang orang yang
sick soul bersifat
pesimistis dan bertabiat
melankolis (Jongeneel, 1987: 88-89). Gordon Allport membagi masyarakat religius ke dalam tipe
instrinsik dan
ekstrinsik. Starbuck mengkaji tentang fenomena
konversi keagamaan. Leube di samping mengkaji tentang
konversi keagamaan juga tentang pengalaman
mistik (Connolly, 2002: 192, 196).
Beberapa sarjana yang mengkaji agama secara psikologis antara lain S. Freud, W. James, Gordon Allport, Carl Jung, Edwin Starbuck, Charcox, Ribot, Janet, Smityh and Fowler, Vande Kemp, dsb. (Whaling, 1984: 27-36).
4. Metode Antropologis.
Metode ini memandang agama dari sudut pandang budaya manusia. Asal-usul dan perkembangan agama dikaitkan dengan budaya manusia (Harsojo, 1984: 221). Biasanya metode ini berjalan sejajar dengan aliran-aliran yang ada dalam antropologi. Misalnya aliran
evolusionisme,
fungsionalisme,
strukturalisme (Daradjat
at. all., 1983: 56-60).
Contoh dari penggunaan metode antropologis ini misalnya: Kajian E.B. Taylor dalam bukunya
Primitive Culture, yang menyimpulkan bahwa menurut evolusi asal-usul agama adalah
animisme. Berikutnya Andrew Lang dalam bukunya
The Making of Religion menyimpulkan bahwa awal agama adalah kepercayaan kepada dewa yang tertinggi. Akhirnya James Frazer dalam bukunya
The Golden Bough menyimpulkan bahwa
magi merupakan agama yang tertua. Marett dalam bukunya
The Threshold of Religion menyimpulkan bahwa pangkal
religi adalah suatu
emosi atau suatu getaran jiwa yang timbul karena kekaguman manusia terhadap hal-hal dan gejala-gejala tertentu yang sifatnya luar biasa (Koentjaraningrat,1980: 46-61).
Beberapa sarjana yang mengkaji agama dengan metode antropologis antara lain: Edward B. Tylor, Andrew Lang, James George Frazer, Robert R. Marett, Wilhelm Schmidt, Arnold vn Gennep, Bronislaw Malinowski, Robert H. Lowie (Waardenburg, 1973: xi, xiii).
5. Metode Fenomenologis.
Metode ini mengkaji agama dari segi essensinya. Dalam metode ini pengkaji agama berusaha mengenyampingkan hal-hal yang bersifat subyektif. Pengkaji agama berusaha mengkaji agama menurut apa yang difahami oleh pemeluknya sendiri, bukan menurut pengkaji agama.
Cara kerja metode ini adalah
mengklasifikasi, menamai, membandingkan dan melukiskan gejala agama dan gejala-gejala agamani tersendiri (tertentu), dengan tidak memberikan penilaian tentang nilai, kenyataan dan kebenaran agama dan gejala-gejala agama tersendiri (tertentu), tetapi menyerahkannya kepada
filsafat agama dan
teologi sistematis. Filsafat agama akan menilainya dalam terang
akal-budi yang murni, sedang teologi sistematis akan menilainya dalam
Penyataan Ilahi atau
Wahyu (Jongeneel, 1978: 106-107).
Contoh dari metode fenomenologis ini misalnya Rudolf Otto dalam bukunya
The Idea of the Holy mengkaji tentang yang
kudus (holy) (Otto, !950: vii-viii). Gerardus van der Leeuw dalam bukunya
Religion in Essence and Manifestation mengkaji tentang
obyek agama,
subyek agama dan obyek dan subyek agama dalam hubungannya satu dengan lainnya (Leeuw, 1963: ix-xii). Mariasusai Dhavamony dalam bukunya
Phenomenology of Religion mengkaji bentuk-bentuk
primitif agama,
obyek agama, agama dan pengungkapannya, pengalaman
religius, dan tujuan agama (Dhavamony, 1995: 11-15). Annemarie Schimmel dalam bukunya
Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam menkaji hal-hal yang
suci dalam Islam: alam dan kebudayaan yang suci, ruang dan waktu yang suci, tindakan yang suci, firman dan kitab suci, individu dan masyarakat suci, Tuhan dan ciptaan-Nya (Schimmel, 1996: 7).
Beberapa sarjana yang mengkaji agama dengan metode fenomenologis antara lain: Ninian Smart, G. Widrengen, Friedrich Heiler, Gustav Mensching, W. Brede Kristensen, C.J. Bleeker, R. Otto, dan Gerardus van der Leeuw (Whaling, 1984: 64-67). Di sini tampaklah beberapa sarjana yang di samping mengkaji agama secara fenomenologis juga historis, yaitu C.J. Bleeker dan G.Widrengen. Hal ini logis, karena metode fenomenologis lahir dari ibu kandung metode historis.
6. Metode Typologis.
Metode ini mengkaji agama atau gejala-gejala agama dengan membuat tipe-tipe tertentu. Di sini gejala-gejala agama yang ruwet disusun dengan
tipe-tipe ideal. Dalam metode ini disusunlah tipe-tipe
mistik,
teologi, peribadatan,
kharisma agama, pemimpin agama, kekuatan agama, kelompok-kelompok agama, kejiwaan pemeluk agama, dsb.
Beberapa sarjana yang menggunakan metode tipologis ini misalnya: Max Weber, Howard Becker, Wiliiam James, Wilhelm Dilthy, Herder, Hegel (Wach, 1961: 26).
7. Metode Perbandingan atau Komparatif.
Dalam metode ini agama secara umum atau gejala-gejala agama (unsur-agama) diperbandingkan satu dengan lainnya. Ada beberapa cara dalam membandingkan ini. Menurut Ake Hultkranz, yang dibandingkan adalah fungsi-fungsi unsur agama dalam konteks budaya. Menurut O. Lewis, perbandingan bisa berupa perbandingan terbatas maupun perbandingan tak terbatas. Menurut Platvoet, perbandingan dapat berupa agama-agama sebagai keseluruhan maupun perbandingan gejala-gejala yang bersamaan di dalam agama-agama. Adapun van Baaren dan Leertouver membedakan antara perbandingan
transkultural dengan perbandingan
kontekstual. Dalam perbandingan transkultural perhatian ditujukan kepada pada cara dan unsur-unsur agama yang dianggap oleh penganut agama tersebut berbeda dengan cara dan unsur agama orang luar. Sedang dalam perbandingan kontekstual agama atau unsur agama dibandingkan dalam situasi konteks agama dan kebudayaan masing-masing. Akhirnya Ake Hulkrantz juga menunjukkan perbandingan melalui prinsip-prinsip sejarah, fungsional, struktural, dsb.(Burhanuddin dan Beck, 1992: 53-56).
Beberapa metode di atas biasanya dikenal sebagai metode yang bersifat ilmiah atau
scientific. A. Mukti Ali menyatakan bahwa metode ilmiah saja tidaklah cukup untuk mendekati agama, perlu dilengkapi dengan metode lain yang khas agama yaitu metode
dogmatis. Oleh karena itu metode yang lengkap unruk mendekati agama adalah
sintesis dari metode ilmiah dan dogmatis yang disebut dengan metode
religio-scientific atau
scientific-cum-doctrinair atau
ilmiah-agamis (Ali, 1993: 79).
Berdasarkan beberapa metode yang digunakan dalam Ilimu Perbandingan Agama di atas (historis, sosiologis, psikologis, antropologis, fenomenologis, typologies, dan komparatif) jelaslah bahwa Ilmu Perbandingan Agama bukan sekedar membanding-bandingkan agama. Ilmu Perbandingan Agama lebih merupakan ilmu yang mengkaji agama secara luas yang bersifat ilmiah atau scientific dengan menggunakan berbagai metode (historis, sosiologis, psikologis, antropologis, fenomenologis, typologies, dan komparativ) dan metode dogmatis sekaligus (ilmiah-agamis). Metode perbandingan atau komparatif hanyalah merupakan salah satu saja dari metode yang dipakai dalam Ilmu Perbandingan Agama. Metode perbandingan atau komparatif yang digunakanpun lebih luas dari persangkaan orang, yaitu sekedar membanding-bandingkan agama. Metode perbandingan yang dipakai dalam Ilmu Perbandingan Agama lebih luas dari pada itu, yaitu mencakup perbandingan fungsi-fungsi unsur agama dalam konteks budaya, perbandingan terbatas dan tak terbatas, perbandingan transkultural dan kontekstual, perbandingan melalui prinsip-prinsip sejarah, fungsional, structural, dsb.